 Lebih 100 perempuan peduli perjuangan mempertahankan tanah dan air akan berkumpul dalam Jambore Perempuan Pejuang Tanah Air pada 14-16 Juli 2017 di Pondok Pesantren Ekologi Ath Thariq, Garut.
Lebih 100 perempuan peduli perjuangan mempertahankan tanah dan air akan berkumpul dalam Jambore Perempuan Pejuang Tanah Air pada 14-16 Juli 2017 di Pondok Pesantren Ekologi Ath Thariq, Garut.
Jambore ini akan menjadi ruang bertukar pengetahuan bagi perempuan dan dukungan kepada perempuan tampil memimpin penyelamatan dan pemulihan tanah air.
Siti Maimunah, peneliti Sayogjo Institute mengatakan, tiga hal utama dalam jambore ini adalah perempuan, perjuangan dan tanah air.
Mengapa? “Kita berada dalam situasi krisis sosial ekologi. Melihat sejarah, dari rezim Soeharto, dengan industri kayu, hingga kini tambang, semua membongkar tanah dan air. Padahal tanah dan air adalah ruang hidup. Perempuan, paling menderita dari eksploitasi sumber daya alam,” katanya.
Jambore ini, merupakan muara dari proses panjang kajian perempuan dan perjuangan membela tanah dan air. Bermula dari kajian Sayogjo Institute pada 2015 di 11 lokasi, mengenai kebutuhan perempuan yang memperjuangkan wilayah mereka dari eksploitasi. Sayogjo Institute, merupakan lembaga yang fokus studi agraria.
Dari kajian itu, ditemukan benang merah bahwa perempuan yang berjuang mengalami titik balik yang mengubah hidup mereka. Perempuan, katanya, juga mengalami halangan berlapis dalam berbagai aktivitas membela lahan mereka.
Dia contohkan, Aleta Baun, perempuan Mollo yang menentang pertambangan marmer di Mollo, Nusa Tenggara Timur. Mama Aleta, begitu biasa disapa, terpaksa berkegiatan malam hari mengumpulkan ibu-ibu di kampungnya. Aleta mengajak ibu-ibu di Mollo menenun di celah bukit yang akan ditambang hingga hampir setahun, sampai dua perusahaan tambang PT. So’e Indah Marmer dan PT. Karya Asta Alam berhenti beroperasi.
Berkat perjuangan itu, Mama Aleta mendapat anugrah Yap Thiam Hien Award pada 2016. Sebelum itu juga menerima penghargaan lingkungan internasional, The Goldman Environmental Prize di San Fransisco, California, Amerika Serikat.
“Karena sering keluar malam, Mama Aleta sering disebut pelacur. Atau Gunarti, perempuan Kendeng yang aktif berjuang menolak pembangunan pabrik semen di Rembang, seringkali dipandang sebelah mata, “Ngapain berjuang? Kan seharusnya jagain anak di rumah.”
Kedua perempuan yang dinilai berhasil memimpin perjuangan mempertahankan tanah air ini akan hadir dalam jambore bersama tiga perempuan lain yang juga berjuang dengan cara masing-masing. Ada Eva Susanti Hanafi Bande, dikenal Eva Bande dipenjara karena membela petani yang melawan perusahaan sawit, PT. Kurnia Luwuk Sejati di Banggai, Sulawesi Tengah.
Ada pula Rusmedia Lumban Gaol atau dikenal dengan panggilan Opung Putra, perempuan asal Desa Pandumaan, Sumatera Utara melawan PT. Toba Pulp Lestari, sebuah perusahaan industri kayu yang mengambil lahan hutan kemenyan.
Ada juga Nissa Wargadipura, yang aktif menjalankan pesantren ekologi Ath Thariq, di Garut, lokasi jambore akan dilaksanakan. Jika kebanyakan pesantren menfokuskan pelajaran santri pada hubungan dengan Tuhan dan manusia, pesantren ini mengajarkan teologi ekologi.
“Kebanyakan lembaga pendidikan sistem individualis, bukan kebersamaan. Ini otokritik dari dibangunnya pesantren ini. Kami menciptakan kader-kader yang bisa mengaitkan pembelajaran hubungan manusia dan alam, dengan ayat-ayat Alquran,” ucap Nissa.
Dengan dampingan ke lima perempuan ini, Sayogjo Institute kemudian memberikan beasiswa Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan (SAPP) kepada 13 pelajar untuk belajar dan tinggal di berbagai wilayah yang mengalami krisis ekologi seperti Aceh Utara, Aceh Selatan, Ogan Komering Ilir, Tojo Una-Una, Donggala, Sigi, Palu, Melawi, Kapuas Hulu, Kutai Kartanegara, Bulungan, Maluku Utara, Tabanan Bali, Bogor, Garut, Flores, Timor Tengah Selatan, Pati, Samarinda, dan Jakarta.

Studi dilakukan selama 1,5 tahun telah berakhir Juni 2017. Peserta beasiswa akan berkumpul dengan peserta jambore lain termasuk ibu rumah tangga, petani, wirausaha, kepala dusun, penulis, pembuat film, pejabat pemerintah untuk bertukar cerita menghadapi krisis sosial ekologi di kampung baik melalui kesaksian, gambar dan narasi.
“Jambore ini juga menyediakan tauladan yang menginspirasi dalam pengelolaan pertanian halaman, pangan mandiri, produk herbal, kerajinan, dan partisipasi perempuan pada pembangunan desa,” kata Mai, koordinator beasiswa SAPP.
Jambore akan dilaksanakan tiga hari, masing-masing membahas pandangan peserta terhadap krisis sosial ekologi pada hari pertama, pembahasan empat topik utama-revolusi meja makan, kewirausahaan hijau, perempuan menganyam, dan kepemimpinan perempuan pada hari kedua.
Hari ketiga lebih banyak melibatkan masyarakat umum menikmati seed art dan terminal benih, wadah pertukaran benih nusantara.
Dari jambore juga diluncurkan berbagai produk pengetahuan yakni Buku Foto: Potret Agraria Perempuan, Buku Putih “Perempuan Merayakan Perjuangan Tanah Air,” Buku Profil kampung halaman : Berjuang Mengubah Nasib, dan Film “Tutur Perempuan Pejuang Tanah Air.”
Babak baru
Eko Cahyono, Direktur Sayogjo Institute, mengatakan, saat ini perjuangan perempuan dan tanah air memasuki babak baru. Jika dahulu perempuan berjuang mengusir penjajah dan mempertahankan ruang hidup di era pembangunan, kini berhadapan dengan neo liberalisme.
“Cirinya ditandai dengan perjuangan-perjuangan perempuan di pedesaan melawan komodifikasi sumber daya alam. Potret ini diwakili dengan krisis ekologi, ditandai ketimpangan yang besar, konflik agraria makin banyak, kerusakan ekologi makin parah,” katanya.
Untuk itu, perlu dukungan berbagi pihak, tak sekadar mengakui perjuangan perempuan ini, namun membantu pemulihan lingkungan misal dengan menciptakan ekonomi tanding.
“Masih sedikit kampanye tentang perjuangan perempuan dan tanah air ini. Jambore ini perlu memperlihatkan itu.”
Pesantren ekologi Ath Thariq, jadi lokasi jambore sebagai simbol salah satu perjuangan mempertahankan ruang hidup perempuan.
“Perempuan bagian dari korban perubahan iklim, karena konflik agraria dan hasil bumi yang tidak dilindungi pemerintah. Dampaknya banyak perempuan tersingkir dari lahan garapan, pergi jauh, minimal ke kota atau menjadi asisten rumah tangga dan tenaga kerja wanita,” kata Nissa.
Pesantren Ath-Thariq hadir sebagai alternatif lembaga pendidikan berbasis perubahan iklim dan mendidik santri dengan perspektif pemulihan alam.
“Dalam situasi ini yang bisa bertahan hanya tanaman lokal. Kami mengadirkan tanaman yang tidak bisa berhenti (tumbuh). Anak-anak diajarkan bagaimana memelihara ekosistem, memelihara ular untuk menyeimbangkan tikus dan menjaga mikroba dalam tanah.”
Kini, di lahan tak lebih satu hektar yang terbagi atas beberapa zona, seperti peternakan, perkebunan dan sawah ini telah menghasilkan dua ton gabah.
“Ini jawaban atas kerentanan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim. Paling aman bagi perempuan adalah menggarap lahan sendiri.”
Sumber :


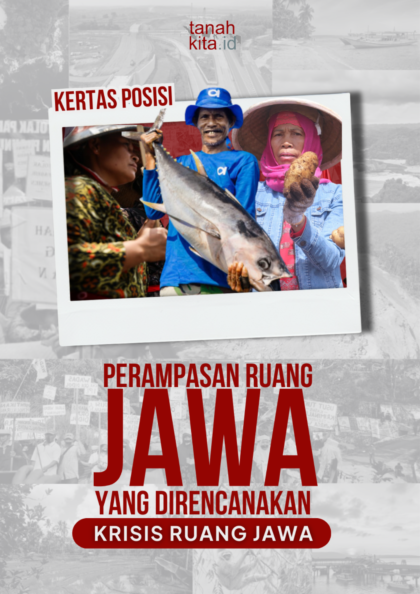













Add Comment